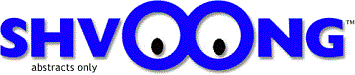Pramoedya Ananta Toer
Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas Pramoedya Ananta Toer (Blora, Jawa Tengah 6 Februari 1925 – Jakarta 30 April 2006) secara luas dianggap sebagai salah satu pengarang yang produktif dalam sejarah sastra Indonesia. Pramoedya telah menghasilkan lebih dari 50 karya dan diterjemahkan ke dalam lebih dari 41 bahasa asing.
Pramoedya Ananta Toer (Blora, Jawa Tengah 6 Februari 1925 – Jakarta 30 April 2006) secara luas dianggap sebagai salah satu pengarang yang produktif dalam sejarah sastra Indonesia. Pramoedya telah menghasilkan lebih dari 50 karya dan diterjemahkan ke dalam lebih dari 41 bahasa asing.Masa Kecil
Pramoedya dilahirkan di Blora, di jantung Pulau Jawa, pada 1925 sebagai anak sulung dalam keluarganya. Ayahnya adalah seorang guru, sedangkan ibunya berdagang nasi.
Nama asli Pramoedya adalah Pramoedya Ananta Mastoer, sebagaimana yang tertulis dalam koleksi cerita pendek semi-otobiografinya yang berjudul Cerita Dari Blora. Karena nama keluarga Mastoer (nama ayahnya) dirasakan terlalu aristokratik, ia menghilangkan awalan Jawa "Mas" dari nama tersebut dan menggunakan "Toer" sebagai nama keluarganya.
Pramoedya menempuh pendidikan pada Sekolah Kejuruan Radio di Surabaya, dan kemudian bekerja sebagai juru ketik untuk surat kabar Jepang di Jakarta selama pendudukan Jepang di Indonesia.
Pasca Kemerdekaan Indonesia
Pada masa kemerdekaan Indonesia, ia mengikuti kelompok militer di Jawa dan kerap ditempatkan di Jakarta pada akhir perang kemerdekaan. Ia menulis cerpen serta buku di sepanjang karir militernya dan ketika dipenjara Belanda di Jakarta pada 1948 dan 1949. Pada 1950-an ia tinggal di Belanda sebagai bagian dari program pertukaran budaya, dan ketika kembali ke Indonesia ia menjadi anggota Lekra, salah satu organisasi sayap kiri di Indonesia. Gaya penulisannya berubah selama masa itu, sebagaimana yang ditunjukkan dalam karyanya Korupsi, fiksi kritik pada pamong praja yang jatuh di atas perangkap korupsi. Hal ini menciptakan friksi antara dia dan pemerintahan Soekarno.
Selama masa itu, ia mulai mempelajari penyiksaan terhadap Tionghoa Indonesia, kemudian pada saat yang sama, ia pun mulai berhubungan erat dengan para penulis di Tiongkok. Khususnya, ia menerbitkan rangkaian surat-menyurat dengan penulis Tionghoa yang membicarakan sejarah Tionghoa di Indonesia, berjudul Hoakiau di Indonesia. Ia merupakan kritikus yang tak mengacuhkan pemerintahan Jawa-sentris pada keperluan dan keinginan dari daerah lain di Indonesia, dan secara terkenal mengusulkan bahwa pemerintahan mesti dipindahkan ke luar Jawa. Pada 1960-an ia ditahan pemerintahan Soeharto karena pandangan pro-Komunis Tiongkoknya. Bukunya dilarang dari peredaran, dan ia ditahan tanpa pengadilan di Nusakambangan di lepas pantai Jawa, dan akhirnya di pulau Buru di kawasan timur Indonesia.
Penahanan dan Masa Setelahnya
Selain pernah ditahan selama 3 tahun pada masa kolonial dan 1 tahun pada masa Orde Lama, selama masa Orde Baru Pramoedya merasakan 14 tahun ditahan sebagai tahanan politik tanpa proses pengadilan.
- 13 Oktober 1965 - Juli 1969
- Juli 1969 - 16 Agustus 1969 di Pulau Nusakambangan
- Agustus 1969 - 12 November 1979 di Pulau Buru
- November - 21 Desember 1979 di Magelang
Pramoedya dibebaskan dari tahanan pada 21 Desember 1979 dan mendapatkan surat pembebasan secara hukum tidak bersalah dan tidak terlibat G30S/PKI, tapi masih dikenakan tahanan rumah di Jakarta hingga 1992, serta tahanan kota dan tahanan negara hingga 1999, dan juga wajib lapor satu kali seminggu ke Kodim Jakarta Timur selama kurang lebih 2 tahun.
Selama masa itu ia menulis Gadis Pantai, novel semi-fiksi lainnya berdasarkan pengalaman neneknya sendiri. Ia juga menulis Nyanyi Sunyi Seorang Bisu (1995), otobiografi berdasarkan tulisan yang ditulisnya untuk putrinya namun tak diizinkan untuk dikirimkan, dan Arus Balik (1995).
Kontroversi
Ketika Pramoedya mendapatkan Ramon Magsaysay Award, 1995, diberitakan sebanyak 26 tokoh sastra Indonesia menulis surat 'protes' ke yayasan Ramon Magsaysay. Mereka tidak setuju, Pramoedya yang dituding sebagai "jubir sekaligus algojo Lekra paling galak, menghantam, menggasak, membantai dan mengganyang" di masa demokrasi terpimpin, tidak pantas diberikan hadiah dan menuntut pencabutan penghargaan yang dianugerahkan kepada Pramoedya.
Tetapi beberapa hari kemudian, Taufik Ismail sebagai pemrakarsa, meralat pemberitaan itu. Katanya, bukan menuntut 'pencabutan', tetapi mengingatkan 'siapa Pramoedya itu'. Katanya, banyak orang tidak mengetahui 'reputasi gelap' Pram dulu. Dan pemberian penghargaan Magsaysay dikatakan sebagai suatu kecerobohan. Tetapi di pihak lain, Mochtar Lubis malah mengancam mengembalikan hadiah Magsaysay yang dianugerahkan padanya di tahun 1958, jika Pram tetap akan dianugerahkan hadiah yang sama.
Lubis juga mengatakan, HB Jassin pun akan mengembalikan hadiah Magsaysay yang pernah diterimanya. Tetapi, ternyata dalam pemberitaan berikutnya, HB Jassin malah mengatakan yang lain sama sekali dari pernyataan Mochtar Lubis.
Dalam berbagai opini-opininya di media, para penandatangan petisi 26 ini merasa sebagai korban dari keadaan pra-1965. Dan mereka menuntut pertanggungan jawab Pram, untuk mengakui dan meminta maaf akan segala peran 'tidak terpuji' pada 'masa paling gelap bagi kreativitas' pada jaman Demokrasi Terpimpin. Pram, kata Mochtar Lubis, memimpin penindasan sesama seniman yang tak sepaham dengannya.
Sementara Pramoedya sendiri menilai segala tulisan dan pidatonya di masa pra-1965 itu tidak lebih dari 'golongan polemik biasa' yang boleh diikuti siapa saja. Dia menyangkal terlibat dalam pelbagai aksi yang 'kelewat jauh'. Dia juga merasa difitnah, ketika dituduh ikut membakar buku segala. Bahkan dia menyarankan agar perkaranya dibawa ke pengadilan saja jika memang materi cukup. Kalau tidak cukup, bawa ke forum terbuka, katanya, tetapi dengan ketentuan saya boleh menjawab dan membela diri, tambahnya.
Semenjak Orde Baru berkuasa, Pramoedya tidak pernah mendapat kebebasan menyuarakan suaranya sendiri, dan telah beberapa kali dirinya diserang dan dikeroyok secara terbuka di koran.
Tetapi dalam pemaparan pelukis Joko Pekik, yang juga pernah menjadi tahanan di Pulau Buru, ia menyebut Pramoedya sebagai 'juru-tulis'. Pekerjaan juru-tulis yang dimaksud oleh Joko Pekik adalah Pramoedya mendapat 'pekerjaan' dari petugas Pulau Buru sebagai tukang ketiknya mereka. Bahkan menurut Joko Pekik, nasib Pramoedya lebih baik dari umumnya tahanan yang ada. Statusnya sebagai tokoh seniman yang oleh media disebar-luaskan secara internasional, menjadikan dia hidup dengan fasilitas yang lumayan - apalagi kalau ada tamu dari 'luar' yang datang pasti Pramoedya akan menjadi 'bintangnya'.
Masa Tua
 Pramoedya telah menulis banyak kolom dan artikel pendek yang mengkritik pemerintahan Indonesia terkini. Ia menulis buku Perawan Remaja dalam Cengkraman Militer, dokumentasi yang ditulis dalam gaya menyedihkan para wanita Jawa yang dipaksa menjadi wanita penghibur selama masa pendudukan Jepang. Semuanya dibawa ke Pulau Buru di mana mereka mengalami kekerasan seksual, mengakhiri tinggal di sana daripada kembali ke Jawa. Pramoedya membuat perkenalannya saat ia sendiri merupakan tahanan politik di Pulau Buru selama masa 1970-an.
Pramoedya telah menulis banyak kolom dan artikel pendek yang mengkritik pemerintahan Indonesia terkini. Ia menulis buku Perawan Remaja dalam Cengkraman Militer, dokumentasi yang ditulis dalam gaya menyedihkan para wanita Jawa yang dipaksa menjadi wanita penghibur selama masa pendudukan Jepang. Semuanya dibawa ke Pulau Buru di mana mereka mengalami kekerasan seksual, mengakhiri tinggal di sana daripada kembali ke Jawa. Pramoedya membuat perkenalannya saat ia sendiri merupakan tahanan politik di Pulau Buru selama masa 1970-an.Banyak dari tulisannya menyentuh tema interaksi antarbudaya; antara Belanda, kerajaan Jawa, orang Jawa secara umum, dan Tionghoa. Banyak dari tulisannya juga semi-otobiografi, di mana ia menggambar pengalamannya sendiri. Ia terus aktif sebagai penulis dan kolumnis.
Ia memperoleh Ramon Magsaysay Award untuk Jurnalisme, Sastra, dan Seni Komunikasi Kreatif 1995. Ia juga telah dipertimbangkan untuk Hadiah Nobel Sastra. Ia juga memenangkan Hadiah Budaya Asia Fukuoka XI 2000 dan pada 2004 Norwegian Authors' Union Award untuk sumbangannya pada sastra dunia. Ia menyelesaikan perjalanan ke Amerika Utara pada 1999 dan memperoleh penghargaan dari Universitas Michigan.
Sampai akhir hayatnya ia aktif menulis, walaupun kesehatannya telah menurun akibat usianya yang lanjut dan kegemarannya merokok. Pada 12 Januari 2006, ia dikabarkan telah dua minggu terbaring sakit di rumahnya di Bojong Gede, Bogor, dan dirawat di rumah sakit. Menurut laporan, Pramoedya menderita diabetes, sesak napas dan jantungnya melemah.
Pada 6 Februari 2006 di Teater Kecil Taman Ismail Marzuki, diadakan pameran khusus tentang sampul buku dari karya Pramoedya. Pameran ini sekaligus hadiah ulang tahun ke-81 untuk Pramoedya. Pameran bertajuk Pram, Buku dan Angkatan Muda menghadirkan sampul-sampul buku yang pernah diterbitkan di mancanegara. Ada sekitar 200 buku yang pernah diterjemahkan ke berbagai bahasa dunia.
Berpulang
 Pada 27 April 2006, Pram sempat tak sadar diri. Pihak keluarga akhirnya memutuskan membawa dia ke RS Sint Carolus hari itu juga. Pram didiagnosis menderita radang paru-paru, penyakit yang selama ini tidak pernah menjangkitinya, ditambah komplikasi ginjal, jantung, dan diabetes.
Pada 27 April 2006, Pram sempat tak sadar diri. Pihak keluarga akhirnya memutuskan membawa dia ke RS Sint Carolus hari itu juga. Pram didiagnosis menderita radang paru-paru, penyakit yang selama ini tidak pernah menjangkitinya, ditambah komplikasi ginjal, jantung, dan diabetes.Pram hanya bertahan tiga hari di rumah sakit. Setelah sadar, dia kembali meminta pulang. Meski permintaan itu tidak direstui dokter, Pram bersikeras ingin pulang. Sabtu 29 April, sekitar pukul 19.00, begitu sampai di rumahnya, kondisinya jauh lebih baik. Meski masih kritis, Pram sudah bisa memiringkan badannya dan menggerak-gerakkan tangannya.
Kondisinya sempat memburuk lagi pada pukul 20.00. Pram masih dapat tersenyum dan mengepalkan tangan ketika sastrawan Eka Budianta menjenguknya. Pram juga tertawa saat dibisiki para penggemar yang menjenguknya bahwa Soeharto masih hidup. Kondisi Pram memang sempat membaik, lalu kritis lagi. Pram kemudian sempat mencopot selang infus dan menyatakan bahwa dirinya sudah sembuh. Dia lantas meminta disuapi havermut dan meminta rokok. Tapi, tentu saja permintaan tersebut tidak diluluskan keluarga. Mereka hanya menempelkan batang rokok di mulut Pram tanpa menyulutnya. Kondisi tersebut bertahan hingga pukul 22.00.
Setelah itu, beberapa kali dia kembali mengalami masa kritis. Pihak keluarga pun memutuskan menggelar tahlilan untuk mendoakan Pram. Pasang surut kondisi Pram tersebut terus berlangsung hingga pukul 02.00. Saat itu, dia menyatakan agar Tuhan segera menjemputnya. "Dorong saja saya," ujarnya. Namun, teman-teman dan kerabat yang menjaga Pram tak lelah memberi semangat hidup. Rumah Pram yang asri tidak hanya dipenuhi anak, cucu, dan cicitnya. Tapi, teman-teman hingga para penggemarnya ikut menunggui Pram.
Kabar meninggalnya Pram sempat tersiar sejak pukul 03.00. Tetangga-tetangga sudah menerima kabar duka tersebut. Namun, pukul 05.00, mereka kembali mendengar bahwa Pram masih hidup. Terakhir, ketika ajal menjemput, Pram sempat mengerang, "Akhiri saja saya. Bakar saya sekarang," katanya.
Pada 30 April 2006 pukul 08.55 Pramoedya wafat dalam usia 81 tahun.
Ratusan pelayat tampak memenuhi rumah dan pekarangan Pram di Jalan Multikarya II No 26, Utan Kayu, Jakarta Timur. Pelayat yang hadir antara lain Sitor Situmorang, Erry Riyana Hardjapamekas, Nurul Arifin dan suami, Usman Hamid, Putu Wijaya, Goenawan Mohamad, Gus Solah, Ratna Sarumpaet, Budiman Sujatmiko, serta puluhan aktivis, sastrawan, dan cendekiawan. Hadir juga Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Jero Wacik. Terlihat sejumlah karangan bunga tanda duka, antara lain dari KontraS, Wapres Jusuf Kalla, artis Happy Salma, pengurus DPD PDI Perjuangan, Dewan Kesenian Jakarta, dan lain-lain. Teman-teman Pram yang pernah ditahan di Pulau Buru juga hadir melayat. Temasuk para anak muda fans Pram.
Jenazah dimandikan pukul 12.30 WIB, lalu disalatkan. Setelah itu, dibawa keluar rumah untuk dimasukkan ke ambulans yang membawa Pram ke TPU Karet Bivak. Terdengar lagu Internationale dan Darah Juang dinyanyikan di antara pelayat.
Penghargaan
- Freedom to Write Award dari PEN American Center, AS, 1988
- Penghargaan dari The Fund for Free Expression, New York, AS, 1989
- Wertheim Award, "for his meritorious services to the struggle for emancipation of Indonesian people", dari The Wertheim Fondation, Leiden, Belanda, 1995
- Ramon Magsaysay Award, "for Journalism, Literature, and Creative Arts, in recognation of his illuminating with briliant stories the historical awakening, and modern experience of Indonesian people", dari Ramon Magsaysay Award Foundation, Manila, Filipina, 1995
- UNESCO Madanjeet Singh Prize, "In recognition of his outstanding contribution to the promotion of tolerance and non-violance" dari UNESCO, Perancis, 1996
- Doctor of Humane Letters, "In recognition of his remarkable imagination and distinguished literary contributions, his example to all who oppose tyranny, and his highly principled struggle for intellectual freedom" dari Universitas Michigan, Madison, AS, 1999
- Chancellor's distinguished Honor Award, "for his outstanding literary archievements and for his contributions to ethnic tolerance and global understanding", dari Universitas California, Berkeley, AS, 1999
- Chevalier de l'Ordre des Arts et des Letters, dari Le Ministre de la Culture et de la Communication Republique, Paris, Perancis, 1999
- New York Foundation for the Arts Award, New York, AS, 2000
- Fukuoka Cultural Grand Prize (Hadiah Budaya Asia Fukuoka), Jepang, 2000
- The Norwegian Authors Union, 2004
- Centenario Pablo Neruda, Chili, 2004
- Anggota Nederland Center, ketika masih di Pulau Buru, 1978
- Anggota kehormatan seumur hidup dari International PEN Australia Center, 1982
- Anggota kehormatan PEN Center, Swedia, 1982
- Anggota kehormatan PEN American Center, AS, 1987
- Deutschsweizeriches PEN member, Zentrum, Swiss, 1988
- International PEN English Center Award, Inggris, 1992
- International PEN Award Association of Writers Zentrum Deutschland, Jerman, 1999
Kecuali judul pertama, semua judul sudah disesuaikan ke dalam Ejaan Yang Disempurnakan.
- Sepoeloeh Kepala Nica (1946), hilang di tangan penerbit Balingka, Pasar Baru, Jakarta, 1947
- Kranji–Bekasi Jatuh (1947), fragmen dari Di Tepi Kali Bekasi
- Perburuan (1950), pemenang sayembara Balai Pustaka, Jakarta, 1949
- Keluarga Gerilya (1950)Subuh (1951), kumpulan 3 cerpen
- Percikan Revolusi (1951), kumpulan cerpen
- Mereka yang Dilumpuhkan (I & II) (1951)
- Bukan Pasarmalam (1951)
- Di Tepi Kali Bekasi (1951), dari sisa naskah yang dirampas Marinir Belanda pada 22 Juli 1947
- Dia yang Menyerah (1951), kemudian dicetak ulang dalam kumpulan cerpen
- Cerita dari Blora (1952), pemenang karya sastra terbaik dari Badan Musyawarah Kebudayaan Nasional, Jakarta, 1953
- Gulat di Jakarta (1953)
 Midah Si Manis Bergigi Emas (1954)
Midah Si Manis Bergigi Emas (1954)- Korupsi (1954)
- Mari Mengarang (1954), tak jelas nasibnya di tangan penerbit
- Cerita Dari Jakarta (1957)
- Cerita Calon Arang (1957)
- Sekali Peristiwa di Banten Selatan (1958)
- Panggil Aku Kartini Saja (I & II, 1963; III & IV dibakar Angkatan Darat pada 13 Oktober 1965
- Kumpulan Karya Kartini, yang pernah diumumkan di berbagai media; dibakar Angkatan Darat pada 13 Oktober 1965
- Wanita Sebelum Kartini; dibakar Angkatan Darat pada 13 Oktober 1965
- Gadis Pantai (1962-65) dalam bentuk cerita bersambung, bagian pertama triologi tentang keluarga Pramoedya; terbit sebagai buku, 1987; dilarang Jaksa Agung. Jilid II & III dibakar Angkatan Darat pada 13 Oktober 1965
- Sejarah Bahasa Indonesia. Satu Percobaan (1964); dibakar Angkatan Darat pada 13 Oktober 1965
- Realisme Sosialis dan Sastra Indonesia (1963)
- Lentera (1965), tak jelas nasibnya di tangan penerbit
- Bumi Manusia (1980); dilarang Jaksa Agung, 1981
- Anak Semua Bangsa (1981); dilarang Jaksa Agung, 1981
- Sikap dan Peran Intelektual di Dunia Ketiga (1981)
- Tempo Doeloe (1982), antologi sastra pra-Indonesia
- Jejak Langkah (1985); dilarang Jaksa Agung, 1985
- Sang Pemula (1985); dilarang Jaksa Agung, 1985
- Hikayat Siti Mariah, (ed.) Hadji Moekti, (1987); dilarang Jaksa Agung, 1987
- Rumah Kaca (1988); dilarang Jaksa Agung, 1988
- Memoar Oei Tjoe Tat, (ed.) Oei Tjoe Tat, (1995); dilarang Jaksa Agung, 1995
- Nyanyi Sunyi Seorang Bisu I (1995); dilarang Jaksa Agung, 1995
- Arus Balik (1995)
- Nyanyi Sunyi Seorang Bisu II (1997)
- Arok Dedes (1999)Mangir (2000)
- Larasati (2000)
- Jalan Raya Pos, Jalan Daendels (2005)
- Pramoedya Ananta Toer dan Karja Seninja, oleh Bahrum Rangkuti (Penerbit Gunung Agung)
- Citra Manusia Indonesia dalam Karya Pramoedya Ananta Toer, oleh A. Teeuw (Pustaka Jaya)
- Pramoedya Ananta Toer dan Sastra Realisme Sosialis, oleh Eka Kurniawan (Gramedia Pustaka Utama)
- Membaca Katrologi Bumi Manusia Pramoedya Ananta Toer, oleh Apsanti Djokosujatno (Tera Indonesia)
- Pramoedya Ananta Toer dan Manifestasi Karya Sastra, Daniel Mahendra, dkk (Penerbit Malka)
 - Biografi Lengkap PRAMOEDYA AT
- Biografi Lengkap PRAMOEDYA AT